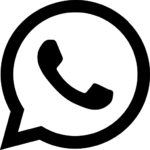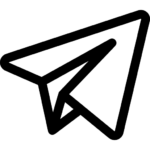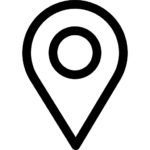[ad_1]
Memosisikan Kuda Anjampiani sebagai pujangga dan bukannya pertapa seperti banyak cerita yang terdengar adalah pilihan cukup jitu. Penulis menjadi lebih leluasa memainkan laku lakonnya, menyuarakan kejernihan sudut pandang, juga leluasa mengisi kisi-kisi kosong dengan cerita-cerita rekaan si pujangga.
Oleh UMAR AFFIQ, Pegiat Komunitas Sastra Malam Minggu di Tuban
—
SEJARAH sering kali tampil dalam wujud tak utuh. Ia seperti guci pecah dan kemudian disusun kembali agar bisa tampil ke wujud semula (sebuah guci).
Namun, hal itu sering kali gagal. Ada pecahan-pecahan yang tak lengkap dan tak mampu dijangkau tangan-tangan sejarawan. Di sinilah, saya pikir karya sastra memiliki ruang untuk menambal apa yang masih berlubang; menggenapi apa yang masih ganjil dari kisah-kisah masa lalu itu. Atau justru sebaliknya?
Seperti halnya novel Kidung Anjampiani karya Bre Redana yang beberapa waktu lalu mendapat anugerah Penghargaan Sastra Kemendikbudristek pada Oktober 2022. Penulis memanfaatkan ruang kosong atas keterbatasan informasi tentang Kuda Anjampiani dan Nambi.
Kuda Anjampiani, putra Ranggalawe, yang hidup menepi dari keratonsentris tentu saja tidak banyak catatan tentangnya. Bahkan, Nambi yang sekalipun adalah mahapatih Majapahit, catatan tentang keluarga dan anak-anaknya masih sangat berkabut. Berbekal dari sinilah –saya kira– penulis memulai pekerjaannya; membangun realitas fiksional. Hal itu jelas dan dipertegas oleh penulis, ”Kisah ini tidak berdasar kenyataan, tapi nyata.” (halaman 50)
Novel ini dibuka dengan satu entakan ritmis; ketika Kuda Anjampiani hanyut dalam mengenang kebersamaannya dengan Ranggalawe pada saat-saat terakhir sebelum berangkat ke medan laga dan akhirnya tewas di Sungai Tambakberas, tiba-tiba ia mendapat undangan untuk menghadap Nambi –rival politik ayahandanya semasa hidup.
Pertanyaan dan terkaan menghadirkan pergolakan batin yang akhirnya melempar Kuda Anjampiani berguru pada Mpu Baraga. Momen ini menjadi titik balik kehidupan Kuda Anjampiani di mana jiwa seorang pujangga dibentuk dan ditempa.
Mulanya, saya mengira novel kecil ini, dengan mengetengahkan Kuda Anjampiani sebagai tokoh pusat cerita, Bre Redana akan menyuarakan kembali suara-suara Ranggalawe yang dimerahkan oleh sejarah dan kekuasaan. Dan, tebakan saya nyaris salah. Sebab, penulis justru hadir sebagai pengamin belaka atas apa yang sudah tercatat dalam buku-buku sejarah.
”Kuda Anjampiani, yang bagaimanapun adalah anak Ranggalawe –anak dari korban ketidakadilan Dyah Wijaya– terdengar begitu lirih. Kalah gemanya sebagai pujangga muda. Di mata penguasa Majapahit, dari saat itu sampai selamanya, ayahanda adalah pemberontak.
Betulkah? Tidak di mataku, bahkan di mata rakyat Tuban. Di mata rakyat Tuban, ayahanda adalah pahlawan, simbol hitam-putih kebenaran. Tak ada wilayah abu-abu bagi benar-salah.” (halaman 2)
Namun, memosisikan Kuda Anjampiani sebagai pujangga –alih-alih sebagai pertapa seperti banyak cerita yang terdengar– nyatanya adalah pilihan cukup jitu. Penulis menjadi lebih leluasa memainkan laku lakonnya, menyuarakan kejernihan sudut pandang, juga leluasa mengisi kisi-kisi kosong dengan cerita-cerita rekaan si pujangga.
Sepanjang alur cerita, pembaca akan menemukan kisah-kisah kecil rekaan aku prosa (Kuda Anjampiani) sebagai peneguh posisi kepujanggaannya. Pembaca akan bertemu dengan cerita Dewi Sanggalangit dari Kediri, dongeng dari Wengker, Arya Umbara pendekar dari Gunung Wilis, Kidung Abhiseka, dan dongeng dari Blambangan.
Kisah-kisah kecil ini tidak muncul begitu saja hanya sebagai cerita karangan Kuda Anjampiani dan terpisah dari alur utama. Tidak. Justru cerita-cerita kecil ini memiliki kaitan dan jalinan untuk melengkapi cerita utama. Di sini pembaca akan dibuat menerka-nerka, sesekali terkejut dan kagum pada waktu bersamaan.
Penulis membawakan ceritanya dengan begitu cair, luwes, dan cukup menghayati peran dan kejiwaan tokohnya. Saking dalamnya penghayatan itu, peristiwa-peristiwa besar seperti pemberontakan Nambi, pemberontakan Ra Kuti, kematian Ra Tanca, dan peristiwa lainnya seolah tidak berarti apa-apa.
***
Jika ditengok dari sisi sumber yang digunakan sebagai pijakan penulisan Kidung Anjampiani, naga-naganya penulis lebih condong ke naskah Pararaton. Ini jelas sekali mengingat bagaimana penulis memunculkan tragedi pemberontakan Lembu Sora pada era Jayanagara, bukan pada era Kertarajasa Jayawardhana.
Namun, obrolan (jika tidak ingin menyebut perdebatan) perlu dibangun di sini tentang tragedi pemberontakan Nambi di Kediri (?). ”Bangkit amarah raja. Dia memerintahkan Mahapati untuk menumpas Nambi. Mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dengan panglima-panglima ternama, tentara Majapahit berangkat ke Kediri untuk menghancurkan Patih Nambi.” (halaman 89)
Memang Nambi memiliki trah darah bangsawan Kediri. Namun, kitab Pararaton maupun Negarakertagama menyebutkan pemberontakan Nambi terjadi di Lamajang (nama lama Lumajang), bukan di Kediri.
***
Bagi pembaca yang cukup akrab dengan tokoh-tokoh era Majapahit, membaca Kidung Anjampiani dan naskah sebelumnya, yaitu Dia Gayatri (Pojok Cerpen, 2020), saya yakin pembaca akan berkerut dahi karena menemukan sesuatu yang rasanya ganjil dan mengganjal, namun tetap nyaman di telinga dan berterima. Ya, itulah siasat Bre Redana. Sebuah trik yang dalam bahasa Bre Redana adalah sebuah proses mengolah kesadaran.
”Mengolah bahasa adalah mengolah kesadaran. … Dengan menjernihkan dan menyucikan bahasa, kita menjernihkan dan menyucikan pikiran dan tubuh.” (halaman 63)
Bre Redana memanfaatkan kemiripan bunyi ”Dyah Gayatri” menjadi ”Dia Gayatri” dan ”Kuda Anjampiani” menjadi ”Kidung Anjampiani”. Dan pada lembar-lembar dalam novel ini penulis tahu betul, bagian mana yang perlu dipermak dan bagian mana yang sebaiknya tetap pada wujud aslinya.
Dalam Kidung Anjampiani, pembaca tak perlu mati-matian mencari lirik-lirik kidung. Sebab, ini bukanlah kitab kidung, melainkan sebuah novel. Meski cukup menarik dengan memasang kata Kidung sebelum nama Anjampiani, tetap saja ia tak bisa disejajarkan dengan Kidung Sorandaka, Kidung Panji Wijayakrama, dan kidung-kidung lainnya. (*)
—
- Judul: Kidung Anjampiani
- Penulis: Bre Redana
- Penerbit: Pojok Cerpen dan Tanda Baca
- Cetakan: Pertama, 2022
- Tebal: x + 141 halaman
- ISBN: 978-623-93977-3-9
[ad_2]
Source link