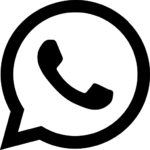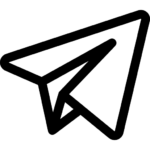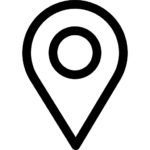[ad_1]
”Mengapa musik India?” Itu pertanyaan banyak orang kepada saya. Pasti itu berkait dengan dua jilid buku yang saya tulis, Aku dan Film India Melawan Dunia (2016), yang kemudian disusul Dawuk (2017). Sebenarnya, karena pembaca juga akan ketemu rock Malaysia di Ulid (2009), kasidah di Kambing dan Hujan (2015), juga orkes Melayu di Anwar Tohari Mencari Mati (2020), pertanyaan yang lebih tepat adalah ”Mengapa musik pop?”
—
UNTUK sampai kepada jawaban atas pertanyaan itu, yang pertama harus dijelaskan adalah: Mengapa musik begitu memengaruhi kepenulisan saya. Dari sini nanti akan tergambar mengapa musik pop kemudian mewakili acuan kebudayaan, identitas, dan idealisasi saya, baik sebagai person maupun sebagai pengarang. Dan, kemudian, baik secara kreatif maupun secara intelektual, menjadi energi besar yang mendorong saya mengarang.
***
Musik untuk saya, pertama-tama, adalah obsesi. Ia adalah lubang besar di dada yang tak kunjung mampu saya tutup. Ia seperti mainan mahal yang dulu tak mampu saya beli, dan sejak itu saya memendam dendam.
Hingga usia ke-15, tak ada perangkat pemutar musik di rumah kami selain radio. Radio memberi saya kebanyakan lagu dangdut yang sedang hit, juga belakangan lagu-lagu India. Sementara ratusan lagu Soneta yang saya hafal di luar kepala nyaris sepenuhnya saya dapat dari musik yang diputar oleh tetangga atau dari pengeras suara orang hajatan (baca: ”Toa dan Budaya (Massa)” [JP, 12/3/22]). Sedangkan kebanyakan lagu pop (cengeng) saya intip dari hasil menonton televisi orang lain.
Ini klise, tapi sepenuhnya benar: kemiskinan membuat musik yang saya sukai tak pernah betul-betul saya miliki, terutama secara fisik. Dan saya pikir bukan saya saja yang punya pengalaman seperti ini.
Puji Tuhan, di masa kuliah, kemajuan zaman menganugerahi orang-orang malang macam saya dengan Mp3. Dengan Mp3, musik menjadi jauh lebih terjangkau. Juga memberi lebih banyak pilihan. Lalu memiliki komputer ketika mulai menjadi buruh memberi saya lemari maya tempat saya menyimpan koleksi lagu-lagu kesukaan.
Namun, saya mesti menunggu masa internet mudah untuk betul-betul melampiaskannya. Saya ingat, ketika untuk kali pertama membeli modem internet sekitar 11 tahun lalu, dalam seminggu saya sudah mengunduh tak kurang dari 2.500 lagu India. Dan sejak itu, berlaku untuk musik jenis lain, saya tak pernah bisa berhenti.
Sebagai obsesi, musik untuk saya tak banyak berbeda dengan, katakanlah, buku, film, dan sepak bola, hal-hal yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan kepengarangan saya. Namun, saya merasa, obsesi ini lebih ”ke dalam”, tak berbeda dengan bapak-bapak kelas menengah melengkapi pajangan boneka Gundam-nya.
Energi kreatif itu baru memuncak keluar ketika saya menyadari bahwa musik yang saya dengarkan dan sukai pada akhirnya menjadi identitas saya, entah itu dikenakan orang lain atau saya kenakan sendiri. Sebagaimana asal usul kedaerahan saya, dialek yang saya pakai, bahkan kulit gelap dan wajah muram saya, saya diidentifikasi dan mengidentifikasi diri dari musik yang saya dengarkan. Dengan kalimat yang lebih ringkas, musik itu adalah saya. Inilah alasan kedua saya.
Musik sebagai identitas itu saya rasakan sejak masih di SMA. Meski masih di region yang sama, preferensi kebudayaan saya dan kebanyakan teman SMA cukup berbeda. Sebagian besar karena tingkat paparan kebudayaan urban yang berbeda –yang sering dipendekkan dalam stereotipe dikotomis ”kota-desa”. Namun di masa kuliah di Jogja-lah, di mana saya menemukan preferensi kebudayaan yang bukan hanya sangat berbeda melainkan juga sangat superior, tapi di saat lain juga menyediakan perangkat untuk mengulitinya (buku-buku, forum diskusi, dan iklim intelektualitas), yang membuat saya bisa meraba di mana preferensi kebudayaan saya berada dan bagaimana hal itu dipandang orang lain.
Di Jogja, saya mendapati musik-musik yang menemani saya tumbuh (dangdut, pop cengeng, kasidah, lagu-lagu India) bukan saja diremehkan, tapi juga asing. Kemunculan band-band berbasis kampus dengan musik humor/pelesetan yang marak di awal 2000-an, yang sebagian besar menjadikan lagu dangdut sebagai objek leluconnya, menegaskan keterasingan itu. Musik-musik itu terasa inferior, sebagaimana diri saya.
Gagal mendorong agar majalah kampus tempat saya berkecimpung mengangkat dangdut sebagai tema liputan, saya mulai menulis cerpen dengan mengutip lirik lagu dangdut (lihat Belajar Mencintai Kambing, 2016). Ketika mulai menulis Ulid pada 2004, tak lama setelah lulus kuliah, saya sudah membayangkan sebuah novel yang mencantumkan lagu ”Katakan Mama” dari Janter Simorangkir dan ”Suci dalam Debu” dari Iklim. Dan sejak itu, untuk setiap novel yang saya tulis, pola tersebut masih terus saya ulang.
Tapi kenapa ada lagu dangdut atau pop cengeng di cerita-cerita yang saya tulis, bukan musik jenis lain –katakanlah musik tradisional, atau jazz, atau klasik? Saya tak punya penjelasan lain kecuali bahwa, sebagai pengarang, saya menempuh cara paling mudah: memungut apa-apa yang sudah saya punya atau apa yang dekat dengan saya. Sebagaimana kisah-kisah, mitos-mitos, pola pikir, juga sistem pengetahuan, demikianlah juga musik itu masuk dalam cerita-cerita saya.
Musik yang mengelilingi dan membesarkan saya, seperti umumnya produk kebudayaan, pada awalnya terberi; saya tak memilihnya. Namun setelah jadi obsesi, juga saya akui/terima sebagai identitas, yang sering kita kacaukan sebagai selera, musik itu tak terpisahkan dengan diri saya. Pada akhirnya itulah yang saya pakai. Kebanyakan untuk alasan teknis. Tapi saya juga tak menampik untuk menggunakannya secara politis. Ini adalah alasan ketiga.
***
Secara teknis, sejauh ini, saya selalu memilih gaya realis untuk bercerita. Saya selalu ingin menulis tokoh-tokoh, kejadian, dan tempat yang dianggap (mendekati) nyata oleh pembaca. Musik pop, karena wataknya yang mudah diasosiasikan dengan tempat, kurun waktu, dan kelompok orang/pendengar tertentu, saya pakai untuk menambah bobot realisme tersebut.
Misalnya, untuk anak desa miskin pada masa Orde Baru, saya tak membayangkan Ulid menyimak ”Barcelona”-nya Fariz RM. Di desa Jawa yang baru memulai proses urbanisasinya pada awal ’90-an, sebuah lagu rock Malaysia jauh lebih masuk akal dibanding album pertama Radiohead. Untuk membual secara meyakinkan di warung kopi di sebuah desa pinggir hutan, Warto Kemplung akan lebih didengarkan jika ia mengutip lagu-lagu Rhoma Irama atau lagu India dibanding menyitir lirik Pink Floyd atau mendendangkan Bob Dylan.
Secara politis, musik pop saya pikir menggambarkan kebanyakan sosok yang saya ceritakan: kebanyakan, rendahan, tak beruntung, tak terhitung, dan, terutama, tak dibicarakan. (*)
*Diolah kembali dari bahan diskusi Nge-Krack Bunyi Ke-6: Mendengar Pendengar, Krack! Studio Jogjakarta, 23 Desember 2022
—
MAHFUD IKHWAN, Penulis asal Lamongan
[ad_2]
Source link