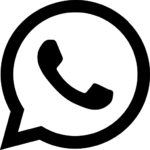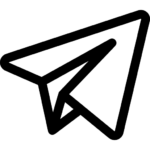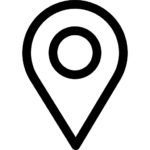[ad_1]
”Ceritakan kepada kami, mengapa kau terus membangkang dan menolak?”
—
DUA lelaki dengan wajah tertutup sudah berdiri di depannya. Kemudian lelaki pertama menghampiri dengan posisi sedikit jongkok. Ia berbisik ke telinga perempuan lansia –Mbok Das sembari menjambak rambutnya pelan-pelan. Bibir lelaki itu menyentuh daun telinga, Mbok Das mendesis dengan mata terpejam. Sementara lelaki kedua memukul-mukul dinding dengan sebatang kayu.
”Sebentar, rasanya suara ini tidak asing.”
Mbok Das membatin, kemudian membuang praduga. Kepalanya merunduk menyentuh lutut, kakinya terlipat menempel dengan dada, duduk di sudut dinding ruang dengan baju basah keringat.
”Lekas katakan agar semua bisa diproses dengan mudah,” bisik lelaki kedua. ”Kalau kau menuruti apa yang kami harapkan, hidupmu akan jauh lebih tenang, bukan?” sambungnya.
”Haaaah…”
Mbok Das meronta. Ia pandang pintu sedikit terbuka. Dari kejauhan ia seperti melihat bayangan anaknya yang pucat dengan tangan terikat. Ia teringat sewaktu dirinya simpuh dan berdoa setiap malam dengan penuh kesedihan, sangat berharap dikaruniai anak. Berkali-kali ia mengelus dada hingga perutnya ketika sedang berada di depan cermin, kemudian suaminya memeluknya dari belakang. Betapa bahagianya ketika penantian yang sangat panjang –di usia pernikahan kelima belas ia dikaruniai keturunan. Ia masih mencoba mengingat suara itu. Praduganya masih menjelajah. Orang-orang hanya mementingkan perut. Otak dan hatinya dilenyapkan oleh kepentingan-kepentingan.
Dua lelaki itu berjalan mundur pelan-pelan, keluar meninggalkan Mbok Das sendirian. Seandainya Mbok Das memiliki kekuatan berkali lipat dari kedua lelaki itu, atau ada belati di sisinya, tanpa pikir panjang akan dihunuskan ke dada mereka satu per satu. Namun sayang, Mbok Das tak banyak tenaga. Ia merelakan kedua lelaki itu pergi begitu saja. Mata lelaki kedua meninggalkan rasa iba, seperti memiliki cinta, bersinar dan bercahaya. Tapi apalah daya, apalah daya…
***
Malam sunyi semakin larut. Kali ini Mbok Das merasa sangat kesepian. Ia merindukan Pagar –suaminya. Ia teringat ketika malam purnama seperti ini, ia diajak suaminya duduk di belakang rumah sembari mengamati bulan yang mengambang di atas perairan Sungai Seruyan. Masih ingat jelas percakapan-percakapan yang sangat susah diruntuhkan dari ingatan.
”Semestinya ini dilakukan anak muda, Das,” suaminya protes.
”Muda bagaimana maksudmu?”
”Iya beromantisan selayak kita ini. Mestinya dilakukan anak muda. Kita sudah tidak lagi waktunya seperti ini.”
”Tidak ada yang salah. Bukankah kita kerap melakukan hal ini?”
”Iya, tapi itu dulu. Mestinya kita sadar diri!”
”Jadi kau berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini salah?”
”Tidak begitu maksudku. Sudah tidak pantas saja!”
”Gar, kaudengar baik-baik. Tatap mataku. Apa yang kita lakukan saat ini adalah semata-mata mengisi energi –ketenangan, ketenteraman, agar kita tetap bahagia. Apa karena wajahku yang sudah menua sehingga kau tak mau lagi melakukan hal ini?”
Mbok Das kali ini sedang sensitif dan manja. Ia menganggap bahwa suaminya sedikit lelah dengan situasi yang ada. Padahal dengan melakukan ritual semacam itu akan menguatkan cintanya. Pandangan Mbok Das terhenti di celah-celah ranting pohon kersen yang lurus ke hamparan sungai. Mendadak ingatan-ingatan itu pudar, ketika dua lelaki mendadak datang memasuki warung.
”Kalian datang dari mana?”
”Dari belakang, Mbok,” Dawan sambil cengengesan.
Mbok Das belum pernah sekali pun melihat mereka. Ia curiga dengan gelagatnya. Tatapan matanya yang liar. Bisik-bisik yang sama sekali tidak bisa ditangkap suaranya oleh Mbok Das. Seperti ada yang sedang disembunyikan.
”Mau makan?”
”Tidak. Kopi saja, Mbok,” ucap Dawan.
”Kau?”
”Sama, Mbok,” ucap Rananto.
Kedua lelaki itu mengamati orang-orang yang lalu-lalang di depan warung. Celingak-celinguk mengamati ruang warung dari sudut ke sudut, atas ke bawah, hingga mendarat mengamati dari ujung rambut sampai mendarat ke pinggul Mbok Das.
”Apa yang kalian cari?”
Mereka gagap, kemudian menyeruput kopinya pelan-pelan dari lepek hingga tandas.
”Kopi dua. Berapa, Mbok?” Dawan tergesa.
”Dua puluh ribu.”
Rananto menyodorkan satu lembar lima puluh ribu tanpa melihat muka Mbok Das.
”Kembaliannya di sini saja, Mbok. Buat besok.”
Kepalanya menoleh ke belakang, kemudian membalikkan badan. Mereka keluar melalui pintu depan samping kanan. Berjalan ke arah utara sangat tergesa. Lenyap begitu saja.
***
”Kau jangan berisik. Tutup mulutmu, Ran,” ucap Dawan.
Langit Borneo, Bilangan Kecik dengan ribuan pohon sawit memerah. Seperti mata babi meronta ketakutan karena berkali-kali dipukul kepalanya menjelang malam ritual memperingati kematian. Barangkali ini sebagai pertanda, sebentar lagi akan ada nasib buruk yang menimpa. Entah, siapa yang akan kejatuhan sial di malam ini. Tentu harus siap menerima dan tetap waspada. Rananto masih diam, dada Dawan masih membara.
”Jangan bodoh karena perempuan lansia. Lagian kau masih nafsu dengan perempuan seperti dia?” sambungnya.
Tubuh Mbok Das sedari sore sudah gemetar. Sepertinya ia memiliki firasat buruk. Ada rasa nyeri yang menjalar di sekujur tubuhnya. Perasaannya tidak keruan. Sebelum anaknya berpamitan pergi ke Jakarta, ia berpesan agar menutup saja warungnya. Sebab tidak baik harus memaksakan kerja, sementara tubuh belum pulih sempurna pascapingsan secara tiba-tiba. Memang dasarnya Mbok Das keras kepala. Ia tetap memaksa membuka warung, bahkan buka lebih awal dari biasanya.
***
Sore itu, bulan lebih awal datang sebelum matahari tenggelam sempurna. Bulan pucat, tampak mengambang di atas perairan. Sepasang karib bercakap.
”Tidak masalah kita berpindah. Uang ganti rugi ini bisa kita buat membeli segalanya,” ucap Asmo kepada karibnya –Pagar.
”Bodoh, kau. Ini tanah kita. Sumber kehidupan. Warisan turun-temurun!”
”Ah, dengan uang yang kaudapatkan, kau bisa gunakan sebagai sumber kehidupan. Kau harus pandai berpikir, dong. Berpikir ke depan. Jauh…” ucap Asmo.
”Ah, kau bercanda, Asmo!”
”Lah, saya serius. Pagar, kautahu,” Asmo memegang pundak Pagar sembari mengernyitkan dahi. ”Uang ganti rugi ini bisa kita gunakan membeli rumah, membuka usaha, makan kalian sehari-hari. Eh, dan kau bisa kawin lagi, Gar!” sambungnya sambil tertawa.
”Sudah gila kau, Mo! Percayalah, suatu ketika nanti, kau akan menyesali apa yang menjadi keputusanmu ini. Tubuhmu akan membara, dan kau tak akan mampu memadamkan, kecuali dengan penyesalan dan air matamu sendiri.”
”Ah, persetan dengan omonganmu, Gar. Aku tak akan bisa hidup dengan kata-katamu itu. Anak dan istriku butuh kehidupan yang lebih baik.”
”Itu pilihanmu, lakukan yang menurutmu baik.”
”Iya, tentu saja. Besok pagi, aku akan menandatangani surat serah terima itu. Siangnya kami –anak dan istri akan pergi ke kota, secepatnya.”
”Iya, di kota nanti, kau akan sulit menemukan ketenteraman dan kesunyian pada malam-malam seperti ini. Berdoalah dengan khidmat sampai Tuhan memberimu kehidupan yang lebih baik. Asal kautahu, kau tak akan pernah mampu menemukan kedamaian seperti ini. Kau tidak akan pernah mendapatkan ruang atau tempat untuk mendekatkan dirimu dengan leluhurmu, mendekatkan dirimu dengan tanah. Sebab ketika kau di kota, kau tidak akan pernah menemukan apa pun dalam kedamaian.”
Asmo hening, sepertinya ia sedang berpikir dan berusaha memikirkan kembali niatnya. Bagaimanapun kesunyian dan ketenteraman sangatlah penting. Sebab sejak kecil mereka sudah diajarkan bagaimana mencintai tanah dan alam yang sebenar-benarnya. Tapi apalah daya, Asmo sudah telanjur mengiyakan dan siap bertemu untuk menandatangani kesepakatan. Ia dengan segera bergelut dengan riuhnya kota.
Tiga hari setelah percakapan itu, Pagar ditemukan tewas mengambang di sungai belakang rumahnya. Mbok Das menjerit memecah tanah. Ketika itu anaknya masih berusia tujuh tahun sedang sakit dan rewel. Tubuh Mbok Das gemetar. Dalam hatinya ia berjanji akan mati-matian menghidupi anaknya agar tidak bodoh dan beringas seperti orang-orang petinggi di ladang.
***
Malam mencekam. Bulan melingkar, sinarnya menyebar di atas perkebunan sawit seluas sebelas ribu hektare. Suara derit jendela dapur warung mengayun-ayun ditempa angin. Dua lelaki masuk ke warung. Warung ini terletak di ujung kanan menjorok ke dalam dari pintu gerbang perkebunan raksasa. Sehingga antara gerbang dan tembok pembatas ini sedikit berkelok ke kanan. Tembok ini sengaja sedikit berkelok setengah lingkaran hanya karena masih ada sisa satu rumah milik Mbok Das yang tidak mau pindah, atau dibeli sampai kapan pun.
Di warung yang menyatu dengan rumah, pada pucuk atap paling depan tertempel kayu ukiran yang menyilang. Jika malam datang, ukiran itu mendadak berpendar. Menyinari batang atap yang berlawanan. Malam ini, di belakang ukiran menyilang itu ada seekor burung yang bertengger. Mata burung itu merah, terlihat sedikit meleleh seperti mau tumpah. Mbok Das masih terus mendengar kabar yang beredar bahwa suaminya mati tenggelam di sungai ketika mencari ikan. Omong kosong!
Ketika itu, orang-orang riuh berdatangan setelah ada anak kecil berteriak sambil menunjuk-nunjuk tubuh yang menonjol tengkurap di atas sungai.
”Duh, gusti, tubuh Pagar.”
Mbok Das menjerit. Ia melihat keganjilan dan belum kuasa menceritakan kepada siapa pun. Ia melihat dua garis lebam melingkar di leher suaminya. Dengan tangan gemetar, Mbok Das mengelus kepala suaminya sebelum dikuburkan. Ia tatap lekat-lekat wajahnya yang pucat.
”Malang sekali nasibmu,” lirih Mbok Das.
Tujuh belas tahun kemudian, ia baru mampu menceritakan semuanya kepada Ariyanto, anaknya. Anaknya merapal dendam. Tubuh perjakanya sudah sangat tampak matang. Ia yakin bahwa ayahnya mati dalam keadaan yang sangat tidak wajar. Sebab ia merasa setelah penolakan untuk menjual tanahnya ke perkebunan itu, nyawa ayahnya melayang begitu saja.
Kuk…kuk…kuk…
Dawan dan Rananto berjalan pelan, mengintip Mbok Das dari balik jendela. Kemudian masuk ke warung dengan wajah semringah.
”Mbok, tidak biasanya sepi seperti ini, ya,” Dawan membuka pembicaraan.
”Ambillah gorengan sampai kau kenyang, Ran. Bila perlu, tambahlah makanmu, mau apa saja, nanti kubayar. Sampai kau benar-benar kenyang, bahkan sampai perutmu tidak mampu menampung makanan-makanan itu,” sambungnya.
”Ah, kau terlalu berlebihan, Wan,” Rananto menyeruput kopinya.
”Hei, apa yang kalian rahasiakan,” ucap Mbok Das.
”Eh, anu sih, Mbok. Nanti malam Mbok Das tidur sama siapa?”
”Sialan kalian.”
Mereka tertawa terbahak-bahak. Tertawa mereka mendadak terhenti ketika mendengar suara burung itu lagi. Kuk…kuk…kuk… Malam semakin sunyi, semakin mencekam. Mbok Das pun turut tenggelam dalam kesunyian hingga berubah menjadi ketakutan.
”Ke mana anakmu pergi, Mbok?” ucap Dawan.
”Kenapa emang?”
”Tidak apa-apa. Tanya saja.”
”Sssttt…jangan bilang siapa-siapa, ya!” Mbok Das berbisik.
”Wah, ini sangat rahasia, Mbok?”
”Iya, aku takut! Sangat takut!”
”Tenang, Mbok. Ada kami untuk melindungimu,” lirih Rananto dengan tatapan penuh cinta.
”Ariyanto ke Jakarta. Entah siapa yang ingin ia temui. Konon, ia ingin mendapatkan keadilan pascatahu bahwa ayahnya meninggal dengan tidak wajar belasan tahun yang lalu. Entahlah, ia kerap sakit kepala dan gelisah memikirkan itu. Bertahun-tahun,” bisik Mbok Das.
Sialnya, mengapa Mbok Das begitu mudah terbuka. Kedua lelaki ini saling menatap. Seperti ada yang mereka rencanakan, seperti ada yang dirahasiakan. Ia paham betul soal kematian Pagar sehingga tak perlu lagi bertanya kapan dan bagaimana kronologinya. Bahkan sampai bertanya apa tujuan anaknya pergi ke Jakarta.
”Kapan anakmu berangkat?”
”Tadi siang.”
Dawan dan Rananto saling menatap. Suasana kembali hening ketika burung itu bersuara kembali. Kedua lelaki itu pergi tergesa dengan muka gelisah. Tiba-tiba menghilang secepat kilat.
***
Ini adalah tahun kedua Ariyanto pergi ke Jakarta tanpa kabar. Tepat di tahun yang sama pula dua lelaki itu tidak pernah lagi tampak batang hidungnya. Mbok Das sudah tidak lagi bertenaga, semakin menua.
Pagi yang riuh, dua lelaki dengan wajah tertutup itu meringkus Mbok Das dengan paksa. Mereka memasukkan Mbok Das ke dalam mobil. Melesat jauh, jauh sekali. Rumah Mbok Das dileburkan, menyatu dengan tanah.
”Lekas! Diam!” ucap dua lelaki saling menimpali. Suara yang semakin berat.
”Suara ini, sepertinya saya mengenalinya,” batin Mbok Das dengan tubuh gemetar. (*)
Tangerang, 22 November 2022
—
AKSAN TAQWIN EMBE, Guru, sastrawan, dan kolumnis. Lahir di Brondong, Lamongan, tinggal di Tangerang. Penerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Sastrawan Berkarya di Wilayah 3T Tahun 2019, Sastrawan Muda Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) Tahun 2018, Borobudur Writers and Cultural Festival Tahun 2018, Ubud Writers and Readers Festival Tahun 2017. Bukunya yang sudah terbit Gadis Pingitan (2014), Melawat ke Seruyan; Mengabadikan Epistolari Perjalanan (2020), Mati yang Menakjubkan (2020). Saat ini bergabung di Komunitas Madah Doa dan mengelola website Tanpabatas.art.
[ad_2]
Source link